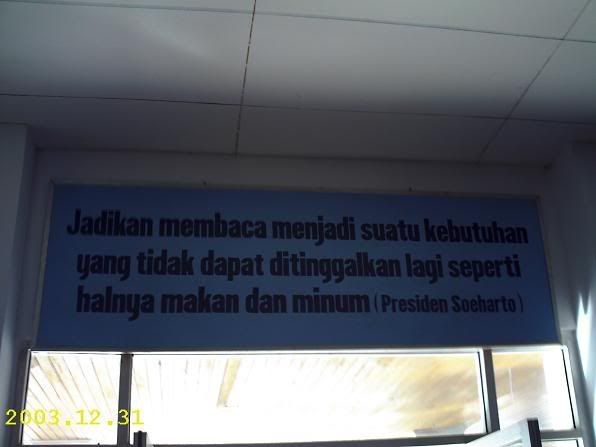Dia mengingatkan saya pada tokoh Adrian Cronauer (diperankan dengan sangat baik oleh aktor humanis Robin Williams), Americans, broadcaster, yang siaran radionya hadir dibarak-barak militer Amerika di perang Vietnam. “Good morning Vietnam…” sapaan khas pembuka siaran yang juga jadi judul film itu (1987) serupa cekat khas gaya dia, “eh, notoga”, lalu terkekeh.
Dia mengingatkan saya pada tokoh Adrian Cronauer (diperankan dengan sangat baik oleh aktor humanis Robin Williams), Americans, broadcaster, yang siaran radionya hadir dibarak-barak militer Amerika di perang Vietnam. “Good morning Vietnam…” sapaan khas pembuka siaran yang juga jadi judul film itu (1987) serupa cekat khas gaya dia, “eh, notoga”, lalu terkekeh.
Kalau Cronauer menyapa pagi, dia sore. Cronauer pemberi semangat bagi tentara AS di pagi hari untuk tetap menjaga militansi dan pemahaman lucu yang ironis tentang perang. Sedang dia pemberi kabar-kabar seputaran kota Palu. Berita kehilangan, kawinan, kematian, apa saja. Seperti ingin mendamaikan setiap senja dari segala kabar. Baik ataupun buruk. Apa saja. Untuk kemudian siap menyambut malam dengan tenang. Dengan biasa-biasa saja. Siapa saja yang mendengar. Keduanya –Cronauer dan dia, percaya apa saja bisa didekati dengan cara yang jenaka.
Waktu kusebut namanya Ayuba Lasira, mungkin tak semua orang dikota ini tahu. Dia lebih dikenal sebagai Om Kota. Dalam sebuah kesempatan bertemu dengannya (16/08) dia bercerita pada saya, dibanyak acara-acara, dia suka menyebut hadirin yang ada sebagai keponakan, hmmm…
Di even-even off air itu, dia adalah master of ceremony yang piawai menggiring suasana berubah cair, tidak protokoler.
Kecil, ringkih, selalu berkopiah, dengan senyum yang selalu terkembang. Om Kota mengawali karirnya pada 1969 di kantor Penerangan Donggala. Pindah ke Radio Republik Indonesia (RRI) pada 1972 sebagai staf operator studio, lalu menghabiskan karir jurnalistiknya yang sejak 1984 sebagai reporter sekaligus penyiar hingga 2006 dibagian pemberitaan RRI.
Reporter sekaligus broadcaster. Keseharian Om Kota adalah melakukan peliputan, sore hari hasil liputan dilaporkan dalam tajuk acara laporan kota, acara yang diasuhnya sejak 1987. Mulai pukul 4 sore dengan durasi sejam. “Laporan kota ini sudah ada sejak 1975. Saya mulai disini sejak 1987 dengan nama Om Kota itu.” Hotman Pontoh. Dia menyebut sebuah nama. Ini orang yang melekatkan nama Om Kota itu padanya. “Dia kepala pemberitaan RRI,” ucap Om Kota pada saya sambil tertawa mengenang.
 Sudah 57 tahun dia sekarang. Setahun lalu (2006) dia pensiun. Tapi dia masih tetap mengudara seperti biasanya. Saya bilang pada dia, ini bukan soal administrasi kepegawaian, tapi ini soal eksistensi sebuah simbol. Seperti bisanya dia, langsung memotong omongan saya, “nuapa vai itu le…” hahaha… kita berdua tertawa bersama-sama diruang tamunya pagi itu. Salah 1 cucunya yang masih balita modar-mandir disitu. “So 3 cucuku le. Dari anakku. 2. Perempuan dua-duanya.”
Sudah 57 tahun dia sekarang. Setahun lalu (2006) dia pensiun. Tapi dia masih tetap mengudara seperti biasanya. Saya bilang pada dia, ini bukan soal administrasi kepegawaian, tapi ini soal eksistensi sebuah simbol. Seperti bisanya dia, langsung memotong omongan saya, “nuapa vai itu le…” hahaha… kita berdua tertawa bersama-sama diruang tamunya pagi itu. Salah 1 cucunya yang masih balita modar-mandir disitu. “So 3 cucuku le. Dari anakku. 2. Perempuan dua-duanya.”
Ya, dia sudah menjadi seperti ikon kota. Mungkin ada yang belum pernah secara fisik bertemu dengannya, tapi mungkin tidak dengan suaranya. Termasuk saya, yang masih kecil suka mendengar suara kalengnya di sirkuit moto-cross tanah runtuh, memandu acara. Tonk Enk, seorang crosser terkenal diganti namanya oleh Om Kota menjadi Tong Sampah. Topik ini begitu berbekasnya pada saya.
Rehat suaranya di laporan kota terjadi kalau dia keluar kota. Even tahunan yang rutin adalah laporan keberangkatan dan kedatangan haji di embarkasi Balikpapan. Ini kegiatan lainnya selain hunting berita, siaran dan ngemsi. Dia bergiat juga dalam proses sosialisasi haji asal Sulawesi Tengah.
Dikenal dimana-mana, untuk urusan plat nomor motornya saja bisa spesial. DN 3450 XX, plat motor bebeknya sebagai identifikasi tanggal, bulan, dan tahun lahirny7a. Hmmm… ini motornya yang ketiga setelah Suzuki A100 dan Yamaha Alfa. Sekarang dia pakai Yamaha FIZ. “Lebe kencang ini,” sambil memegang sadel. Tertawa lagi. Baru saja dicuci pagi itu. Motor itu diparkir diruang tamu didepan sofa tempat kami duduk.
Tentang ikon itu, dia menyamakannya dengan Kang Ibing untuk kota Bandung. Tapi buat sebagian orang lain yang dekat dengan kesehariannya beraktivitas, eksistensi ikon itu pelan-pelan digerus. Saya menangkap curhatnya. Mungkin karena sudah pensiun itu. Dia mengeluh soal akses mendapatkan berita dari narasumber yang ingin dia temui. Kebanyakan petinggi. Protokoler suka menghalang-halangi. Untuk itu dia suka kritik waktu siaran. Tapi dengan jenaka. “Gubernur saja saya kritik. Contohnya waktu acara hari ulang tahun Donggala. Beliau tidak datang.” Dia juga kritik situasi sekarang. Terlebih soal kebebasan pers yang menurutnya kelebihan pers.
Berita apa yang paling dia hindari untuk disampaikan? Informasi pemadaman bergilir dari PLN. Hmmm… dia pernah dimarah-marah via telepon karena informasi yang keliru. Padahal tentu saja bukan salah dia. Dia hanya membaca informasi dari humas PLN jalan-jalan dan daerah mana saja dikota ini yang akan dipadamkan.
Yang ingin melihatnya dilayar kaca, setiap Jumat sore hingga magrib, dia live di TVRI Sulteng dalam acara ATM, akronim dari Ayuba, Tasrif, Midu, acara talkshow yang menghadirkan pembicara yang berkait tema diskusi.
Dia, dan Cronauer adalah pemberi kabar. Keduanya true story. Beda zaman dan situasi. Sama spiritnya, jenaka.
Sore harinya, ibu saya yang sering mendengar siarannya menyetel radio. Suara sirene memanjang. Lalu tawa kecil mengikuti.
Foto: Ayuba Lasira (NeMu), Cronauer (http://vietnamresearch.com/media/afvn/adrian.jpg), cover Robin Williams (http://www.moviehabit.com/photos/good_morning_vietnam_150.jpg)